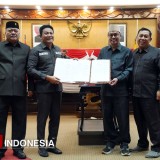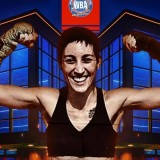TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kasus yang menjerat Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, telah menjadi salah satu peristiwa paling membingungkan dalam lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di tengah ambisi negara memperkuat BUMN dan mengakselerasi inovasi layanan publik, muncul ironi ketika seorang pemimpin yang mengambil langkah strategis justru berakhir di kursi pesakitan. Apakah ini benar-benar korupsi, atau sebuah pengabdian yang berubah menjadi kriminalisasi?
Akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh ASDP pada 2019–2022 menjadi inti persoalan. ASDP membeli saham PT JN sebesar Rp892 miliar dan 11 kapal afiliasinya senilai Rp380 miliar, dengan total transaksi sekitar Rp1,272 triliun.
KPK menuding proses ini cacat prosedur, tidak cermat dalam analisis risiko, serta menghasilkan kerugian negara sebesar Rp893,16 miliar. Hakim Tipikor bahkan menyebut kerugian mencapai Rp1,25 triliun berdasarkan metode net loss selisih antara uang yang dikeluarkan dengan nilai wajar aset menurut audit.
Dalih utamanya: kapal-kapal yang diakuisisi dinilai tua, tidak layak beroperasi, dan membebani ASDP. Sebagian bahkan disebut telah terparkir di galangan karena urusan perbaikan belum tuntas. Atas dasar itu, Ira divonis 4,5 tahun penjara.
Yang menarik, hakim juga menegaskan tidak ada bukti bahwa Ira menikmati keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. Tidak ada uang suap. Tidak ada aliran dana gelap. Tidak ada korupsi dalam makna lazimnya: memperkaya diri.
Di sinilah muncul perdebatan publik. Para pendukung Ira menilai keputusan akuisisi PT JN merupakan langkah bisnis strategis yang bertujuan memperkuat fungsi transportasi penyeberangan nasional, terutama rute-rute terpencil (3T).
Dengan mengakuisisi perusahaan beserta izin operasi dan 53 kapal yang dimilikinya, ASDP dapat memperluas jangkauan layanan, memperkuat subsidi silang antarrute, dan mendongkrak pangsa pasar.
Ira membela diri: ASDP “membeli perusahaan, bukan kapal”. Artinya, nilai akuisisi tidak berdiri pada fisik kapal saja, melainkan struktur bisnis, izin operasi, potensi ekspansi, dan posisi strategis PT JN di pasar penyeberangan nasional. Harga yang dibayar, menurutnya, hanya sekitar 60% dari total nilai aset.
Masalahnya, perhitungan nilai wajar versi auditor, KPK, dan pengadilan sangat berbeda dari perhitungan internal dan konsultan yang digunakan ASDP. Ketimpangan metodologi inilah yang lalu berubah menjadi dasar kriminalisasi.
Bagi penegak hukum, persoalannya bukan semata salah hitung. KPK menilai prosedur akuisisi dipenuhi revisi keputusan direksi yang tidak semestinya, analisis risiko yang dikesampingkan, serta penilaian aset yang dianggap manipulatif. Dengan kata lain, kasus ini bukan kegagalan bisnis melainkan tindakan melawan hukum.
Tetapi bagi sebagian publik, terutama kalangan profesional BUMN, vonis ini justru menimbulkan efek gentar: apakah setiap inovasi yang gagal harus berakhir sebagai perkara pidana?
Inilah akar dilemanya. Negara membutuhkan pemimpin BUMN yang berani mengambil risiko besar demi transformasi layanan publik. Namun ketika risiko itu tidak terwujud sesuai rencana, mereka bisa diseret ke pengadilan hanya karena perbedaan tafsir nilai aset.
Perlu disadari bahwa dunia bisnis tidak pernah berjalan dengan kepastian absolut. Setiap keputusan strategis selalu mengandung ketidakpastian. Jika setiap kegagalan dimaknai sebagai korupsi, maka BUMN akan dikelola dengan mental paling konservatif: aman di atas kertas, tetapi mandek dalam inovasi.
Kasus Ira mengajarkan satu hal mendasar: Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh dalam metodologi audit kerugian negara. Penilaian aset tidak boleh hanya bergerak di atas rumus hitungan statis, tetapi harus memuat konteks operasional, potensi jangka panjang, strategi ekspansi, dan risiko yang memang melekat pada bisnis. Ketimpangan metodologi audit yang terlalu teknokratis justru berpotensi menghukum orang yang berniat baik.
BUMN juga harus memiliki mekanisme perlindungan hukum bagi para profesional yang mengambil keputusan strategis tanpa motif pribadi. Tanpa itu, keberanian dan inovasi akan mati di tangan ketakutan.
Selain itu, penegakan hukum juga wajib membedakan secara tegas antara kesalahan manajerial dengan korupsi. Dalam prinsip hukum modern, niat jahat tetap merupakan elemen penting. Jika tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada suap, tidak ada permufakatan gelap, maka konteks pengambilan keputusan harus dilihat lebih proporsional.
Keputusan memenjarakan Ira Puspadewi tidak bisa dibaca hanya sebagai kemenangan pemberantasan korupsi. Ia mencerminkan masalah lebih dalam mengenai bagaimana hukum ekonomi negara bekerja serta bagaimana negara memperlakukan para pemimpin yang mengambil risiko untuk memperbaiki sistem.
Di satu sisi, KPK dan hakim menjalankan mandat menjaga keuangan negara. Tetapi di sisi lain, putusan ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah Indonesia sedang menghukum korupsi, atau sedang menghukum keberanian?
Jika negara ingin BUMN berlari lebih cepat, mengambil ruang pasar yang lebih besar, dan memperluas layanan publik hingga ke daerah terpencil, maka hukum harus mampu membedakan mana risiko bisnis, mana penyalahgunaan kekuasaan.
Ira Puspadewi kini menjadi simbol dilema itu. Ia bukan sekadar seorang terdakwa, melainkan cermin dari ketegangan antara akuntabilitas dan inovasi.
Indonesia membutuhkan hukum yang adil, transparan, dan cukup cerdas untuk tidak mematikan keberanian orang-orang yang bekerja untuk negara. Sebab bangsa ini tidak akan maju jika setiap langkah besar dibalas dengan jeruji besi.
***
*) Oleh : Ahmad Fizal Fakhri, S.Pd., Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Professor at Uinsa, LP Ma'arif Jatim Book Writing Team.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |