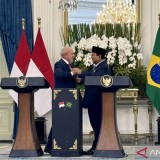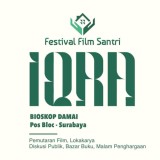TIMES SURABAYA, SURABAYA – Salah satu pilar penting pendidikan di Indonesia bukan sekadar sebagai tempat menimba ilmu agama, melainkan juga sebagai institusi pembentukan karakter, sosial dan budaya tidak lain tidak bukan adalah Pesantren.
Memasuki era modern dengan tantangan digital, ekonomi kreatif, dan globalisasi, pertanyaan muncul: apakah pesantren hanya akan tetap seperti “museum tradisi”, atau bisa menjadi motor perubahan peradaban?
Di sinilah peran santri menjadi kunci. Generasi yang menginternalisasi nilai-nilai pesantren sekaligus mampu membaca arus kemajuan.
Dengan data terkini menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren telah mencapai puluhan ribu lembaga menurut Kementerian Agama Republik Indonesia tercatat 42.433 pondok pesantren aktif pada 2024/2025. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren dan santri bukan hanya bagian dari sejarah, tapi bagian dari masa depan bangsa.
Memahami skala keberadaan pesantren penting agar kita menyadari besarnya tuntutan dan peluang yang terbuka. Data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2020/2021 tercatat 9.310 pesantren di Jawa Barat saja, dan secara nasional jumlah pesantren mencapai 36.600 lembaga pada 2022.
Sementara itu, data lain mencatat bahwa jumlah santri di Jawa Timur pada tahun 2022/2023 saja mencapai 992.889 santri. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pesantren secara nasional bukan lagi fenomena kecil, melainkan bagian dari struktur pendidikan dan sosial yang sangat besar.
Dengan demikian, perubahan yang terjadi di dalam pesantren akan memiliki dampak yang luas bukan hanya bagi santri dan kiai, tetapi bagi masyarakat dan peradaban secara keseluruhan.
Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter dan Nilai
Kelebihan pesantren yang paling khas adalah kemampuannya membentuk karakter melalui kehidupan bersama, pengajian kitab, asrama, dan pembiasaan ibadah. Ini bukan hanya soal aspek kognitif, melainkan pembentukan moral, etika, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Santri dalam lingkungan pesantren belajar hidup bersama berbagi ruang, menjalankan rutinitas keagamaan, dan berdialog dengan kiai serta sesama santri.
Semua ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai luhur yang sering sulit diperoleh di luar lingkungan pesantren. Di tengah perubahan sosial yang cepat, karakter ini menjadi fondasi penting agar kemajuan teknologi atau ekonomi tidak menjadi destruktif tetapi produktif dan manusiawi.
Meski memiliki potensi besar, pesantren menghadapi tantangan real yang tidak boleh diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur dan akses teknologi: banyak pesantren di daerah terpencil yang masih kesulitan konektivitas internet, sarana komputer, atau fasilitas pembelajaran modern.
Tantangan berikutnya adalah kurikulum: pola pendidikan tradisional fokus pada kitab dan pengajian belum sepenuhnya dikombinasikan dengan keterampilan abad-21 seperti literasi digital, kewirausahaan, komputasi, dan inovasi sosial.
Sebuah artikel Kemenag menyebut bahwa dari sekitar 39.551 pesantren dengan 4,9 juta santri (data semester ganjil 2023/2024) masih banyak lembaga yang belum mendapatkan program kemandirian pesantren secara optimal.Tanpa adaptasi, pesantren berisiko ketinggalan dalam arus perubahan, dan santri bisa menjadi objek transformasi, bukan subjeknya.
Santri dalam Gerakan Perubahan Sosial dan Ekonomi
Santri tidak hanya sebagai penerima pendidikan, tetapi dapat menjadi agen perubahan. Banyak pesantren kini mulai mengembangkan program kewirausahaan, kegiatan ekonomi sosial, dan layanan masyarakat yang dioperasikan oleh santri dan alumni.
Lingkungan pesantren yang berada di masyarakat menjadikan santri sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas: mereka bisa mempraktikkan nilai pesantren dalam kehidupan nyata serta ikut memecahkan masalah sosial lokal seperti kemiskinan, rendahnya literasi, pengangguran, dan disrupsi teknologi.
Dengan demikian, santri berpotensi menjadi pionir pemberdayaan lokal yang berakar pada nilai etika dan spiritual. Transformasi ini memungkinkan pesantren tidak hanya menjaga warisan, tetapi juga memproduksi inovasi yang relevan dengan zaman.
Peradaban dapat dipahami sebagai sistem nilai, institusi, budaya, dan teknologi yang menghasilkan kemajuan manusiawi dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, pesantren memiliki potensi sebagai laboratorium: mereka menggabungkan aspek pengajaran agama, sosial, dan komunitas dan kini semakin banyak yang menggabungkan aspek teknologi, ekonomi, dan layanan publik.
Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, fungsi pesantren diperluas sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Melalui fungsi pengembangan masyarakat, banyak pesantren kini menjalankan unit usaha, koperasi, pertanian terintegrasi dan proyek teknologi sosial yang melibatkan santri dan warga sekitar.
Model seperti ini menunjukkan bahwa pesantren bisa menjadi pionir peradaban yang memadukan iman, ilmu, kerja, dan pengabdian sosial. Santri, sebagai generasi penerus, memiliki peran penting dalam mengoperasionalkan model ini: dari menguasai tradisi pengajian hingga menjadi pelaku inovasi.
Agar pesantren menjadi agen perubahan, santri harus mampu menjembatani tradisi dan teknologi. Ini bukan berarti meninggalkan tradisi keilmuan klasik seperti kitab kuning atau pengajian sorogan, tetapi mengembangkan kompetensi baru: literasi digital, pemahaman data, kewirausahaan berbasis nilai, dan pemikiran kritis.
Santri yang menguasai teknologi akan mampu memanfaatkan media sosial untuk dakwah positif, mengembangkan startup berbasis pesantren, atau memanfaatkan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan bersama.
Hal ini membutuhkan dukungan: akses pelatihan, bahan ajar yang relevan, dan lingkungan pesantren yang terbuka terhadap inovasi tanpa kehilangan identitas. Dengan demikian, santri bisa menjadi pelaksana konkret perubahan bukan hanya mengikuti arus, tetapi memimpin.
Transformasi pesantren dan santri tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pesantren, pemerintah, sektor swasta, akademia, dan masyarakat sipil.
Pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan, anggaran, dan infrastruktur; swasta dan industri teknologi bisa membuka akses pasar dan peluang kerja; akademia bisa memberikan riset dan kurikulum; pesantren sendiri harus aktif menyesuaikan budaya internal dan menyusun strategi inovasi.
Sebagai contoh, program Kemandirian Pesantren yang dicatat Kemenag telah menjangkau sekitar 3.600 pesantren dari target 5.000. Kebijakan yang tepat akan memperkuat posisi pesantren sebagai bagian dari sistem nasional pembangunan, dan santri sebagai pelaku utama di lapangan.
Pesantren, perubahan, dan peradaban bukan sekadar tiga kata: mereka adalah rangkaian yang saling terkait dan saling memperkuat. Pesantren akan berhasil berkontribusi pada peradaban masa depan jika mampu merespon perubahan dengan luwes tanpa kehilangan akarnya.
Santri akan menjadi tulang punggung proses itu jika mereka dilengkapi dengan ilmu, karakter, dan visi. Sebaliknya, bila pesantren dan santri hanya bertahan di format lama tanpa adaptasi, maka mereka berisiko tertinggal bahkan terpinggirkan.
Menyongsong Hari Santri, sudah saatnya menjadikan momentum bukan hanya untuk peringatan, tetapi untuk komitmen nyata: memperkuat pesantren, memperkuat santri, dan bersama-sama membangun peradaban Indonesia yang beradab, mandiri, dan berdaya.
***
*) Oleh : Ahmad Fizal Fakhri, S.Pd., Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Professor at Uinsa, LP Ma'arif Jatim Book Writing Team.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |