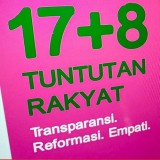TIMES SURABAYA, SURABAYA – Dalam beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh lompatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang bukan hanya menyentuh aspek teknis kehidupan, tetapi juga secara radikal mengubah cara kita berkomunikasi, berpikir, dan membentuk makna.
Dari chatbot yang bisa menulis puisi, avatar digital yang bisa menjadi MC acara adat, hingga algoritma yang menentukan informasi apa yang layak muncul di layar kita, semua ini mengindikasikan bahwa komunikasi hari ini tidak lagi sekadar soal pesan dan media, melainkan tentang relasi kuasa baru antara manusia, mesin, dan makna.
Sayangnya, banyak teori komunikasi yang kita pelajari di kampus-kampus masih mengandalkan paradigma lama: bahwa media mengirim pesan, audiens menerima, dan makna terbentuk secara satu arah. Teori-teori ini dibangun dalam era televisi, radio, dan surat kabar, yang kini semakin ditinggalkan.
Bagaimana mungkin kita masih bicara soal efek media secara linear, padahal hari ini audiens juga adalah kreator? Bagaimana kita bisa bicara soal ruang publik rasional ala Habermas, sementara ruang digital dipenuhi oleh komentar bot, polarisasi politik, dan perang afeksi?
Kehadiran kecerdasan buatan (AI), atau yang semakin tepat disebut sebagai Akal Imitasi, kian menyingkap betapa sempitnya kerangka teori-teori komunikasi lama dalam memahami relasi makna di zaman kini.
Kita tidak lagi berada dalam lanskap komunikasi manusia ke manusia, melainkan telah melangkah ke era kompleks manusia–mesin–makna, di mana makna tidak hanya dikirim dan diterima, tetapi diproduksi ulang oleh sistem algoritmik yang tidak terlihat, tidak netral, dan sering kali melampaui kendali manusia itu sendiri.
AI tidak sekadar memfasilitasi komunikasi, dia kini juga menghasilkan makna, membingkai persepsi, dan bahkan, dalam banyak kasus, memanipulasi narasi. Algoritma TikTok, misalnya, bisa membuat tradisi selametan atau larung sesaji mendadak viral bukan karena nilai spiritualnya, melainkan karena kecocokan visualnya dengan selera hiburan digital.
ChatGPT atau sistem sejenis dapat menjawab pertanyaan tentang sejarah, agama, atau politik dengan kalimat yang rapi dan meyakinkan, meskipun biasnya bisa terselip halus, mengikuti pola-pola data mayoritas.
Contoh terbaru yang menunjukkan ketegangan ini datang dari kompetisi pemrograman internasional, di mana Prszemyslaw Debiak, seorang programmer asal Polandia, berhasil unggul tipis dari sistem AI dalam tantangan pemecahan masalah Coding dan algoritma.
Kemenangan manusia atas mesin ini menjadi peristiwa langka, sekaligus membuktikan dua hal: pertama, bahwa manusia masih memiliki celah kreativitas dan intuisi yang belum bisa sepenuhnya ditiru mesin.
Kedua, bahwa mesin telah berada di titik yang sangat dekat untuk mengalahkan manusia secara konsisten. Maka kemenangan Debiak bukanlah kemenangan yang menenangkan, melainkan peringatan bahwa Akal Imitasi telah tumbuh sedemikian cepat, mendekati batas yang dulu kita anggap tak terlampaui.
Di tengah semua ini, pertanyaan mendesak yang harus diajukan bukan lagi “seberapa canggih AI?”, melainkan “siapa kini yang menguasai produksi makna?”. Jika yang menentukan apa yang layak dilihat, dibaca, atau diyakini adalah sistem tak terlihat yang diatur berdasarkan logika keterlibatan, viralitas, dan preferensi pasar, maka teori komunikasi yang masih bicara soal pengirim, saluran, penerima dalam garis lurus sudah tidak relevan.
Kita memerlukan pembacaan ulang yang lebih reflektif, kritis, dan politis terhadap bagaimana makna dimediasi, diproses, dan diotomatiskan, dan apa implikasinya bagi masyarakat, budaya, dan demokrasi.
Di sinilah letak urgensi mencabar teori: bukan untuk menolak warisan keilmuan, tetapi untuk memperbarui lensa kita dalam memahami kenyataan yang telah berubah secara radikal.
Teori komunikasi tidak bisa lagi berhenti pada model linear seperti SMCR (Source–Message–Channel–Receiver) dari Berlo, atau model efek peluru seperti Hypodermic Needle Theory yang seolah menempatkan audiens sebagai objek pasif.
Bahkan Agenda Setting Theory, yang selama ini menjadi acuan banyak lembaga media dan dosen komunikasi, kini mulai terbatas karena gagal menjelaskan bagaimana AI dan algoritma yang menentukan agenda, bukan sekadar redaktur atau jurnalis.
Dalam dunia digital, di mana informasi dibanjiri oleh jutaan konten setiap detik, dan makna dibentuk melalui visualisasi, afeksi, serta keterpajangan algoritmik, maka paradigma komunikasi yang lama perlu digeser.
Kita kini membutuhkan teori komunikasi yang tidak hanya berbicara tentang pesan, saluran, dan efek, sebagaimana diwariskan oleh model-model klasik, tetapi juga yang mampu menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dipertukarkan dalam ekosistem digital yang dikendalikan oleh sistem otomatis.
Kita perlu pendekatan yang bisa menelaah bagaimana makna tidak lagi dikontrol hanya oleh manusia, tetapi oleh mesin yang diprogram untuk mengenali pola, mengkalkulasi probabilitas afeksi, dan menyajikan konten berdasarkan logika keterlibatan.
Dalam konteks ini, teori komunikasi tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dikatakan atau bagaimana dikatakan, tetapi juga siapa yang mengendalikan keterlihatan dan mengapa konten tertentu menjadi dominan secara visual dan afektif.
Beberapa teori modern seperti Participatory Culture dari Henry Jenkins dan Networked Publics dari Dana Boyd memang telah memperluas pemahaman kita tentang peran aktif pengguna dan transformasi ruang publik di era digital.
Namun, teori-teori ini cenderung memandang partisipasi sebagai bentuk emansipasi, tanpa cukup menelaah bagaimana partisipasi itu sendiri telah dikomodifikasi dan dikendalikan oleh struktur algoritmik. Bahkan dalam kerangka Algorithmic Gatekeeping yang dikembangkan oleh Zeynep Tufekci dan Tarleton Gillespie.
Meski sudah membongkar bagaimana algoritma menjadi penentu visibilitas informasi, masih ada sisi-sisi yang luput: seperti bagaimana algoritma tersebut digunakan oleh negara untuk membangun citra, atau bagaimana estetika visual yang diatur oleh AI mampu merekayasa afeksi publik secara massal.
Demikian pula dengan artikel jurnal mengenai Affective Publics oleh Zizi Papacharissi yang sangat membantu memahami ledakan ekspresi emosional dalam ruang digital. Teori ini menjelaskan bagaimana emosi berperan dalam pembentukan ruang publik modern.
Namun belum secara penuh menjangkau bagaimana emosi itu juga sedang disimulasikan oleh mesin, dengan video AI yang menyentuh, wajah pahlawan yang dibuat tampan, dan narasi sejarah yang direkonstruksi agar “terasa menyentuh”.
Bahkan teori Reading of Image dari Kress dan van Leeuwen pun, yang menawarkan kerangka penting untuk membaca gambar, suara, dan teks secara simultan, perlu diperluas lagi dalam konteks ketika visual itu sendiri kini diproduksi oleh mesin, bukan oleh manusia sebagai pembuat makna utama.
Kita juga tak bisa mengabaikan Digital Capitalism dari Christian Fuchs, yang menyoroti dominasi korporasi teknologi global dalam mengekstrak nilai dari partisipasi digital pengguna. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks negara-negara berkembang, kapitalisme digital tidak selalu digerakkan oleh pasar bebas atau korporasi raksasa.
Pemerintah daerah, lembaga negara, bahkan institusi budaya juga kini aktif memproduksi konten digital demi akumulasi kapital simbolik, bukan ekonomi. Maka, teori sekaliber Fuchs pun perlu dibuka ulang, dikritisi, dan disesuaikan dengan realitas lokal dan hibridisasi kuasa di ruang digital.
Contoh yang paling nyata adalah ketika tren-tren populer seperti “Naruto kalau jadi pekerja kantoran di Indonesia”, atau “wajah pahlawan nasional versi AI” membanjiri media sosial. Lewat teknologi akal imitasi, wajah tokoh-tokoh Sejarah, dari Raden Wijaya sampai Cut Nyak Dien, direkonstruksi secara sinematik seolah-olah mereka hidup di era kontemporer.
Dalam satu sentuhan klik, sejarah dijinakkan, identitas dikonstruksi ulang, dan imajinasi publik diarahkan oleh visualisasi yang tampak meyakinkan, padahal sepenuhnya spekulatif. Hal yang sama terjadi pada tren visualisasi karakter anime dalam konteks profesi lokal.
Walaupun tampak lucu dan kreatif, semua itu menunjukkan bagaimana AI kini berperan sebagai produsen realitas visual, yang dalam banyak kasus jauh lebih dipercaya daripada data historis atau narasi akademik. Komunikasi tak lagi tentang menyampaikan kebenaran, tapi tentang membentuk persepsi melalui kesan yang meyakinkan.
Lebih dari itu, teori komunikasi masa depan harus mampu menjelaskan mengapa negara, bukan hanya korporasi teknologi, kini juga menjadi produsen utama citra budaya. Pemerintah daerah, kementerian, bahkan aparat kini ikut bermain dalam ranah visual: menyusun narasi, memilih estetika, dan memanipulasi persepsi melalui konten digital.
Maka, mencabar teori adalah langkah penting untuk membuka jalan baru dalam memahami komunikasi bukan sekadar proses teknis, tapi sebagai perjuangan makna dalam dunia yang dipenuhi ilusi, data, dan akal imitasi.
Masyarakat Indonesia berhak tahu bahwa kecanggihan teknologi hari ini juga membawa risiko. Kita bukan hanya berhadapan dengan mesin, tapi juga dengan sistem makna yang semakin tidak kita sadari.
Karena itu, melek media hari ini bukan hanya soal tahu hoaks atau tidak, tapi juga tahu bagaimana citra dibentuk, untuk siapa, dan dengan cara apa. Pendidikan komunikasi masa depan tidak cukup hanya mengajarkan teori lama, tapi harus melatih kesadaran kritis, empati digital, dan kemampuan membaca ulang kenyataan di balik layar.
Jadi, kalau kita ingin tetap relevan dalam dunia yang berubah cepat ini, kita tidak hanya perlu update aplikasi. Kita juga perlu update cara berpikir. Karena di era AI, yang tidak berubah bukan hanya akan ketinggalan, tapi bisa salah membaca dunia.
Dengan demikian, mencabar teori bukanlah tanda pembangkangan terhadap ilmu, melainkan bentuk keberanian epistemik untuk tetap relevan dan kontekstual. Bahkan teori-teori paling modern sekalipun tak kebal dari kebutuhan untuk dikaji ulang.
Karena di dunia yang bergerak cepat, teori yang tak dicabar akan menjadi dogma. Dan dogma dalam ilmu komunikasi hanya akan membuat kita gagal memahami bagaimana makna dibentuk dan didistribusikan di era akal imitasi ini. (*)
***
*) Oleh : Arif Budi Prasetya, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dan Mahasiswa Doktoral Universitas Airlangga.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |