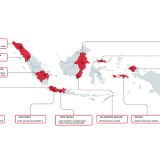TIMES SURABAYA, MALANG – Peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, kembali memantik perdebatan lama. Apakah pesantren masih menyimpan praktik feodalisme yang memperbudak santri?
Narasi itu kembali menguat di media sosial, bersamaan dengan beredarnya video santri mencium tangan kiai, berjalan jongkok di hadapan pengasuh, hingga membantu membersihkan atau membangun pondok. Dari situ muncul tudingan bahwa pesantren adalah lembaga “feodal” yang menempatkan santri sebagai pelayan kiai.
Namun tudingan semacam itu sejatinya lahir dari kesalahpahaman terhadap sistem pendidikan pesantren sebuah sistem yang sudah berumur ratusan tahun dan berakar kuat dalam tradisi keilmuan Nusantara. Pesantren bukan tempat perbudakan, melainkan lembaga pendidikan yang membentuk manusia secara utuh: dengan ilmu, adab, dan spiritualitas.
Tradisi seperti mencium tangan kiai, berjalan sopan, atau membantu pekerjaan pondok bukan bentuk penindasan. Itu adalah ekspresi penghormatan kepada guru dan simbol latihan tanggung jawab sosial.
Santri membersihkan kamar, memasak, menimba air, atau bahkan ikut membantu pembangunan pondok bukan karena diperintah secara sepihak, melainkan sebagai bagian dari pembelajaran hidup bersama menumbuhkan kemandirian, rasa gotong-royong, dan disiplin diri.
Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda Quraisy: “Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu.” Begitu pula Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menulis bahwa ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan, sedangkan adab tanpa ilmu tetap membawa kebijaksanaan.
KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, melalui karyanya Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim menegaskan bahwa keberkahan ilmu hanya akan datang dari sikap hormat murid kepada gurunya. Di pesantren, nilai-nilai inilah yang dihidupkan bukan relasi kuasa, tapi relasi keberkahan.
Jika pesantren dianggap feodal, mengapa kepercayaan masyarakat terhadapnya terus meningkat? Data Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 42 ribu pesantren aktif dengan 11 juta santri di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, sekitar 52 persen pesantren masih menjaga sistem tradisional (salaf) yang fokus pada pengajian kitab, sementara sisanya telah mengintegrasikan pendidikan formal modern.
Di Jawa Timur saja, terdapat ribuan pesantren dengan hampir satu juta santri angka yang menunjukkan bahwa pesantren bukan lembaga pinggiran, melainkan pilar penting dalam sistem pendidikan nasional.
Ambil contoh di Kabupaten Malang, terdapat lebih dari 800 pesantren dengan ribuan santri aktif. Mereka bukan hanya belajar agama, tapi juga keterampilan hidup dan ekonomi.
Di banyak pesantren, santri diajak berwirausaha, mengelola pertanian, hingga menjalankan unit bisnis mandiri. Ini membuktikan bahwa pesantren adalah lembaga yang adaptif dan kontributif, bukan sekadar tempat belajar kitab kuning, apalagi simbol feodalisme.
Pesantren bahkan menjadi fondasi sejarah kebangsaan. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren adalah basis perjuangan. KH. Hasyim Asy’ari di Tebuireng dan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta membangun pergerakan sosial melalui lembaga pendidikan. Dari tangan merekalah lahir dua organisasi besar: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang hingga kini menjadi motor sosial dan moral bangsa.
Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari adalah bukti nyata bagaimana pesantren berperan langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Semangat jihad melawan penjajah itu kini diabadikan sebagai Hari Santri Nasional. Dari sana kita belajar bahwa pesantren tidak pernah memelihara feodalisme; ia justru menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan.
Banyak tokoh besar lahir dari rahim pesantren. Presiden keempat RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tumbuh dalam tradisi Tebuireng yang kuat dengan nilai keilmuan dan kemanusiaan. KH. Sahal Mahfudz dari Kajen dikenal sebagai ulama intelektual yang memperjuangkan ekonomi kerakyatan.
KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI saat ini, juga merupakan produk murni pesantren. Mereka adalah bukti bahwa sistem pendidikan berbasis adab dan keikhlasan justru melahirkan generasi pemimpin bangsa yang berwawasan luas dan berjiwa sosial tinggi.
Pesantren, dengan segala tradisinya, memang tidak seperti sekolah modern. Di pesantren, ilmu bukan sekadar data atau hafalan, tetapi cahaya yang harus dijaga dengan akhlak. Santri tidak diajari untuk menantang guru, tetapi untuk menyerap ilmu dengan hati yang tunduk. Nilai-nilai semacam ini justru menjadi benteng moral di tengah arus globalisasi yang sering mengikis etika dan kesantunan.
Sayangnya, sebagian orang menilai tradisi pesantren dengan kacamata modernisme barat yang serba rasional dan egaliter. Padahal, pendidikan tidak bisa diukur dengan satu paradigma. Di pesantren, hierarki bukan untuk menindas, tetapi untuk mendidik.
Rasa hormat kepada guru bukanlah bentuk perbudakan, melainkan cara menjaga barokah ilmu sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi dirasakan nyata oleh mereka yang pernah menjadi santri.
Lebih jauh, pesantren juga menjadi motor pemberdayaan masyarakat. Banyak pesantren yang kini memiliki koperasi, bank mikro, usaha kuliner, pertanian, hingga lembaga riset.
Pesantren tak hanya mencetak ulama, tapi juga wirausahawan sosial. Mereka membangun ekonomi dari bawah dengan nilai-nilai kejujuran dan keberkahan, sebuah praktik ekonomi yang berakar pada ajaran Islam dan budaya lokal.
Karena itu, menuduh pesantren sebagai lembaga feodal adalah bentuk ketidakadilan intelektual. Pesantren bukan tempat eksploitasi, melainkan ruang transformasi. Di dalamnya, santri belajar menjadi manusia beradab, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari lingkungan yang sederhana itulah, lahir tokoh-tokoh yang membawa perubahan besar bagi bangsa ini.
Adab, ilmu, dan kontribusi tiga pilar inilah yang membuat pesantren tetap relevan di setiap zaman. Di saat dunia modern kehilangan arah moral, pesantren justru hadir sebagai penjaga nurani bangsa. Ia mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa adab hanyalah kesombongan, dan kekuasaan tanpa moral hanyalah tirani.
Maka sebelum menuding pesantren feodal, barangkali kita perlu belajar lebih dalam: bahwa di balik kesederhanaannya, pesantren sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar pengetahuan yakni kemanusiaan itu sendiri.
***
*) Oleh : Husnul Hakim, S.Y., M.H., Dekan FISIP UNIRA Malang dan Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |