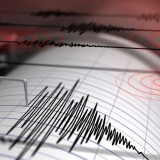TIMES SURABAYA, SURABAYA – Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Data BNPB per 8 Desember 2025, menunjukkan dampak yang sangat luas: 941 jiwa meninggal, 268 orang hilang, lebih dari 5.000 orang terluka, serta 156.500 rumah mengalami kerusakan.
Bencana ini juga merusak 1.200 fasilitas umum, 420 rumah ibadah, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, dan 435 jembatan, dengan total 52 kabupaten terdampak lintas provinsi.
Besarnya korban, cakupan wilayah, dan kerusakan infrastruktur tersebut menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah telah terlampaui. Dalam kondisi demikian, negara tak kunjung menetapkannya sebagai Bencana Nasional
Karena itu, langkah hukum yang bisa ditempuh bukan lagi menunggu kebijakan turun dari langit birokrasi, tetapi menggunakan mekanisme yang tersedia dalam negara hukum itu sendiri, yakni gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS). Jalan hukum ini layak ditempuh bukan sebagai langkah radikal, tetapi sebagai instrumen korektif yang paling rasional ketika pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional.
Melalui CLS, warga negara dapat menuntut pemulihan tata kelola negara, memaksa hakim menguji apakah ketidaktegasan pemerintah telah melanggar asas due diligence, prinsip state responsibility, dan kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa.
Parameter Bencana: Dari UU 24/2007 Menuju Kewajiban Konstitusional Negara
Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana bukanlah ruang diskresi absolut yang dibiarkan tanpa batas.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah menetapkan lima parameter objektif untuk menentukan apakah suatu peristiwa harus dinyatakan sebagai bencana nasional: jumlah korban, kerugian ekonomi, tingkat kerusakan sarana-prasarana, cakupan wilayah, serta dampak sosial-ekonomi.
Tidak satu pun dari parameter tersebut mengharuskan angka tertentu secara numerik; yang menjadi ukuran esensial adalah apakah kapasitas daerah telah terlampaui. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional bukan “hadiah” politik dari pusat, melainkan kewajiban hukum yang melekat ketika indikator hukum terbukti terpenuhi.
Kendati demikian, dalam praktiknya, negara sering berlindung di balik narasi teknokratis bahwa penetapan bencana nasional adalah pertimbangan policy, sehingga tak dapat dipaksa kecuali oleh presiden sendiri. Pandangan semacam ini tampak nyaman, namun tidak akurat secara hukum.
Ketika warga negara mengalami kerugian sistemik, sementara pemerintah tidak memenuhi kewajiban kehati-hatian (duty of care), Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, serta Kovenan Internasional yang telah diratifikasi, justru menempatkan negara sebagai pihak yang wajib memastikan perlindungan atas hak hidup, kesehatan, lingkungan sehat, dan rasa aman. Keterlambatan penetapan status bencana nasional, ketika unsur-unsur empiris telah terpenuhi, dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian konstitusional.
Sebagaimana dirumuskan dalam doktrin kelalaian, terdapat lima unsur yang harus diuji: (a) adanya perbuatan atau pembiaran; (b) adanya kewajiban kehati-hatian; (c) tidak dijalankannya kewajiban tersebut; (d) timbulnya kerugian; dan (e) hubungan kausal antara pembiaran dan kerugian. Semua unsur ini relevan ketika pemerintah tidak segera menempatkan krisis dalam kategori “bencana nasional”, padahal kapasitas daerah telah runtuh.
Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, apa yang tampak sebagai “keterlambatan administratif” sebenarnya merupakan pelanggaran kewajiban konstitusional untuk melindungi martabat manusia. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat merupakan tujuan utama negara hukum: tindakan pemerintah wajib berlandaskan HAM, bukan sekadar kalkulasi politik.
Penyelenggara negara tidak cukup sekadar hadir; ia harus hadir tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat tindakan. Kegagalan dalam memenuhi standar itu membuka ruang bagi warga untuk menuntutnya secara hukum.
Citizen Lawsuit sebagai Hak Gugat Warga Negara
Dalam rezim negara hukum modern, warga negara bukan hanya objek kebijakan publik; mereka adalah subjek yang berhak menggugat ketika negara gagal menjalankan kewajibannya. Mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) merupakan ekspresi yuridis dari transformasi ini: sebuah instrumen yang memungkinkan warga menggugat pemerintah tanpa harus membuktikan kerugian langsung, sepanjang tindakan atau pembiaran negara menimbulkan ancaman atau akibat bagi kepentingan publik.
CLS memiliki karakteristik pokok yang sangat relevan untuk mempersoalkan kegagalan penetapan bencana nasional: ia memberi akses langsung bagi warga mewakili kepentingan publik, melindungi masyarakat, serta memungkinkan gugatan atas pelanggaran kewajiban konstitusional. Tidak seperti class action, CLS tidak memerlukan kerugian individual; yang diuji adalah kelalaian negara sebagai penyelenggara kekuasaan.
Landasan yuridisnya bukanlah norma tunggal, tetapi korpus hukum yang saling terkait: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU 39/1999 tentang HAM, serta dua Kovenan Internasional (ICESCR dan ICCPR) yang telah diratifikasi. Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 100 UU HAM semakin menegaskan hak warga untuk menggugat ketika negara lalai memberikan perlindungan atau pelayanan publik yang layak.
Dalam konteks bencana, CLS menjadi mekanisme yang tepat bahkan satu-satunya mekanisme untuk memaksa negara menjalankan kewajibannya. Sebab, penetapan bencana nasional tidak memiliki ranah judicial review ke Mahkamah Agung atau uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi.
Satu-satunya celah hukum adalah menggugat Presiden melalui CLS atas dasar pembiaran yang menyebabkan kerugian publik, dengan petitum memerintahkan pemerintah menetapkan status bencana nasional atau menjalankan kewajiban penanggulangan sesuai UU 24/2007.
Putusan PN Palangkaraya (CLS Kebakaran Hutan 2015) yang diperkuat oleh PT Palangkaraya, memperlihatkan bahwa pengadilan dapat menyatakan pemerintah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak optimal melaksanakan kewajiban penanggulangan bencana ekologis. Walaupun tidak semua tuntutan dikabulkan, esensi hukumnya jelas: Negara tidak kebal atas kelalaian kolektifnya ketika menyangkut keselamatan publik.
CLS juga didukung oleh empat prinsip penting yang dikemukakan Hadjon: pemberdayaan konstitusi, pembentukan virtuous citizen, mekanisme respons kepentingan publik, dan kebajikan sebagai dasar tindakan pemerintah. Ketika pemerintah gagal mengamalkan prinsip ini, CLS menjadi jalan korektif yang sah secara hukum.
Karena itu, menggugat Presiden melalui CLS bukanlah tindakan “melawan negara”, melainkan cara paling konstitusional untuk “memaksa negara” memenuhi hak publik agar terlayani dengan baik. Justru ketika pemerintah bersikap pasif, warga negara yang bertindak menempuh CLS sedang menjalankan perannya dalam negara hukum modern: memastikan konstitusi bekerja, memastikan hak publik tidak dibiarkan menguap, dan memastikan tragedi kemanusiaan tidak diperlakukan sebagai statistik administratif. Bagaimana Pendapat Anda?
***
*) Oleh : Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |