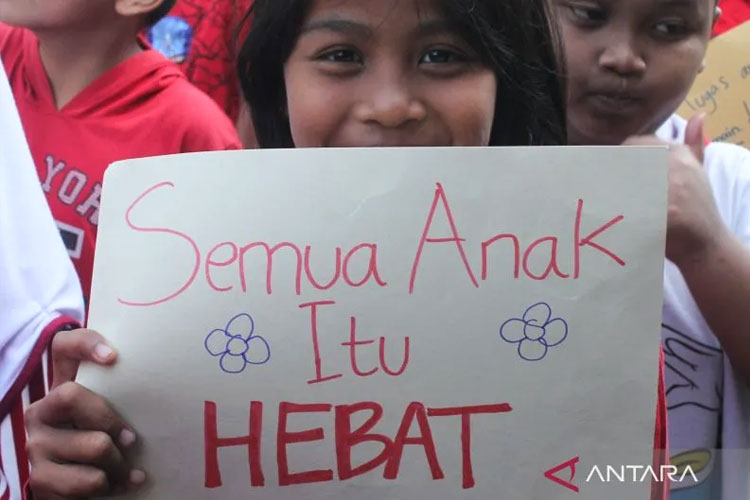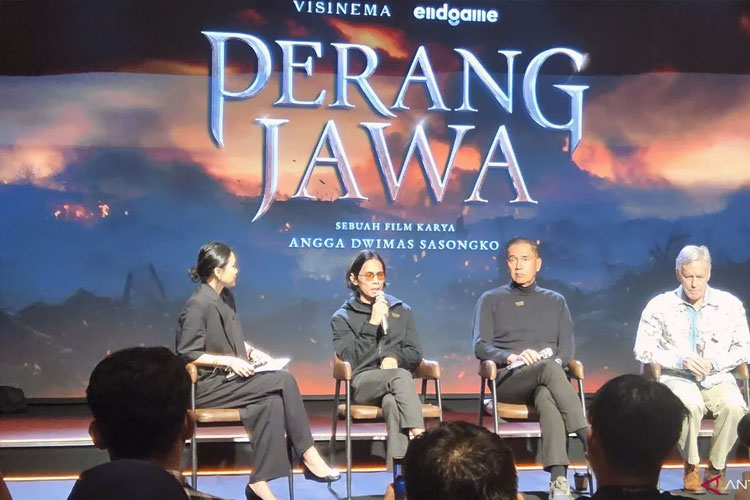TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketika pasukan Thailand dan Kamboja memperkuat penjagaan perbatasan dan isu klaim wilayah kembali memanas, yang tidak kalah tajam dari misil adalah narasi. Di balik manuver militer dan diplomasi yang terlihat di panggung internasional, terdapat pertempuran lain yang tak kalah sengit, yakni perebutan legitimasi melalui media dan komunikasi digital.
Konflik geopolitik hari ini bukan lagi sekadar urusan peluru atau strategi pertahanan, ia juga menjelma dalam bentuk kompetisi membingkai kebenaran, menyusun sejarah, dan menyebar pengaruh melalui layar gawai kita masing-masing.
Perseteruan antara Thailand dan Kamboja terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear sesungguhnya telah berlangsung lama, namun kini memperoleh dimensi baru dengan hadirnya media sosial dan platform digital sebagai arena pertarungan narasi.
Masing-masing negara tidak hanya berdebat soal garis batas, tetapi juga berlomba menanamkan makna, siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih sah, siapa yang patut didukung.
Wacana “invasi budaya”, “pencaplokan sejarah”, atau “pengkhianatan diplomatik” merebak dalam judul-judul berita nasionalis. Ini bukan semata laporan, melainkan konstruksi: framing naratif yang dirancang untuk membentuk kesetiaan publik domestik.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi politik hari ini tak lagi bersandar pada pidato-pidato formal atau konferensi pers, melainkan pada kemampuan negara dalam mengelola persepsi melalui viralitas.
Di ruang digital, negara-negara kini memiliki pasukan baru: para buzzer nasionalis, influencer yang membalut propaganda dengan konten ringan, bahkan bot yang menyebar informasi secara otomatis.
Ketika potongan video diedit sedemikian rupa dan disebarkan secara sistematis, dia bukan lagi sekadar informasi, tetapi senjata. Inilah yang disebut sebagai propaganda digital: sebuah orkestrasi komunikasi yang secara halus namun efektif menggiring opini publik tanpa disadari.
Di tengah derasnya arus informasi ini, publik bukan lagi sekadar pemirsa. Mereka ikut serta sebagai produsen, distributor, bahkan pejuang digital. Unggahan ulang, dan komentar yang menggiring narasi menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Ini membuat batas antara negara, warganya, dan medianya menjadi kabur. Kekuasaan menjadi cair, tetapi sekaligus lebih mudah dimanipulasi.
Ironisnya, konflik Thailand–Kamboja menjadi cermin dari krisis komunikasi regional yang lebih struktural dan mendalam. ASEAN, organisasi kawasan yang selama ini dibanggakan karena prinsip non-intervensi dan jargon “stabilitas kawasan”, justru tampak gagap dalam menyediakan mekanisme komunikasi lintas negara yang efektif, cepat, dan kredibel.
Tidak ada ruang dialog digital yang mampu meredam eskalasi narasi. Tidak ada forum publik bersama yang bisa memfasilitasi klarifikasi atau debunking atas informasi yang berpotensi memicu konflik.
Sebaliknya, yang terjadi adalah fragmentasi informasi: ruang media dipetak-petakkan oleh kepentingan nasional masing-masing negara, membiarkan warga terjebak dalam algoritma etnosentris yang memperkuat prasangka dan menyulut sentimen permusuhan.
Ketiadaan mekanisme komunikasi bersama ini menjadi celah berbahaya. Saat framing satu negara dibiarkan mendominasi tanpa koreksi atau jembatan lintas narasi, konflik dengan mudah dikapitalisasi oleh elite politik atau aktor digital yang memang ingin menyalakan api.
Di sinilah perang perbatasan tidak lagi hanya soal wilayah, tetapi tentang siapa yang menang dalam membingkai siapa korban, siapa agresor, dan siapa yang paling “patriotik”.
Disinformasi menjadi pelumas kekerasan simbolik, dan nasionalisme sempit menjadi bahan bakar konflik yang terus menyala tanpa arah penyelesaian.
Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, tidak bisa terus-menerus memainkan peran “penjaga etika regional” tanpa tindakan konkret. Apalagi kita sendiri memiliki potensi konflik laten: dari perairan Natuna yang kerap bergesekan dan timbul konflik, isu Papua yang terus menjadi bahan framing internasional, hingga perebutan narasi budaya yang dengan mudah meledak di media sosial.
Indonesia berisiko menjadi target sekaligus pelaku perang narasi jika tidak bersiap. Tanpa intervensi serius di bidang komunikasi publik regional, ASEAN berpotensi berubah dari kawasan damai menjadi ladang pertempuran naratif yang berkepanjangan, di mana konflik tidak dimediasi, tetapi didiamkan dan dibiarkan membusuk menjadi kebencian kolektif.
Dalam skenario terburuk, perang narasi ini bisa berkembang menjadi ketegangan politik yang memicu mobilisasi militer. Dan ketika itu terjadi, perdamaian ASEAN yang selama ini dibanggakan hanya akan menjadi kenangan manis dari masa lalu yang gagal dipertahankan oleh kesadaran komunikatif bersama.
Jika dilihat secara global, konflik Thailand–Kamboja bukan sekadar riak kecil di kawasan Asia Tenggara, melainkan bagian dari gelombang besar eskalasi geopolitik yang mengkhawatirkan.
Setelah pecahnya perang Rusia–Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Iran–Israel, dunia saat ini menyaksikan bagaimana api konflik perbatasan menyebar ke berbagai titik strategis dengan pola yang menyerupai spiral krisis global.
Semenanjung Korea terus berada di ambang perang, situasi di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan semakin bergejolak, dan kini Asia Tenggara ikut memanas, bukan hanya oleh kepentingan lokal, tapi juga oleh pengaruh kekuatan besar dunia yang bermain di balik layar narasi. Banyak analis menyebut bahwa lanskap ini mengarah pada kondisi pra–Perang Dunia ke-3.
Namun berbeda dengan masa lalu, eskalasi saat ini tidak selalu ditandai oleh deklarasi perang resmi atau mobilisasi pasukan terbuka. Perang hari ini dimulai dengan friksi wacana, viralnya ujaran kebencian, dan akumulasi kebencian digital yang sistemik dan lintas batas.
Platform media sosial menjadi ladang pertempuran baru, di mana propaganda, disinformasi, dan framing ideologis menyusup ke kesadaran publik tanpa perlu menembakkan satu peluru pun.
Media internasional tidak tinggal diam. Mereka bukan hanya peliput, tapi juga pemain aktif dalam kontestasi narasi global. CNN dan Reuters, misalnya, cenderung mengedepankan narasi nasionalisme Thailand dengan membingkai konflik dalam konteks “kedaulatan wilayah”.
Sementara itu, media milik pemerintah Kamboja membangun wacana tentang “penjajahan sejarah” dan marginalisasi identitas lokal. Narasi yang dikonstruksi ini tidak pernah netral, masing-masing media membawa serta agenda politik, ekonomi, dan aliansi diplomatik dari negara dan institusi yang mereka representasikan.
Dalam konteks ini, publik internasional bukan sedang “menerima informasi”, tetapi disuguhi realitas yang telah dikurasi dan dikendalikan. Berita bukan sekadar laporan, tetapi konstruksi; narasi bukan sekadar fakta, tapi senjata. Inilah titik di mana komunikasi berubah menjadi medan yang penuh jebakan simbolik.
Ketika perang tak lagi bergantung pada senjata, tapi pada siapa yang berhasil menciptakan musuh dan korban dalam benak publik global, maka dunia sedang menuju bentuk baru konflik yang lebih tersembunyi, lebih sunyi, namun sangat merusak.
Di sinilah urgensi kajian ilmu komunikasi menemukan relevansinya. Komunikasi, dalam kerangka kritis, bukan sekadar soal menyampaikan pesan, melainkan soal siapa yang punya kuasa atas makna.
Konflik seperti Thailand–Kamboja bukan hanya pertikaian batas teritorial, tapi juga arena untuk memperebutkan siapa yang berhak mendefinisikan sejarah, identitas, dan kebenaran.
Dalam konteks ini, komunikasi berubah menjadi medan perang yang lebih sunyi, tapi tidak kalah mematikan. Makna bisa menjadi peluru simbolik, dan framing bisa menjadi alat kekerasan struktural yang menciptakan musuh-musuh imajiner di benak publik. Media, baik lokal, nasional, maupun internasional, tidak lagi netral.
Mereka bukan sekadar memotret kenyataan, tapi juga ikut memproduksinya. Narasi tentang “penjaga kedaulatan” atau “pihak yang tertindas” bukan hadir begitu saja, melainkan hasil konstruksi diskursif yang sarat ideologi.
Ketika negara, media, dan warga saling bersaing membingkai siapa korban dan siapa agresor, maka pertempuran sesungguhnya telah berpindah dari medan fisik ke lanskap kognitif dan psikologis.
Konflik hari ini tak lagi harus memicu suara ledakan, menimbulkan asap mesiu, atau menyisakan bangkai senjata di medan perang. Cukup dengan mengatur alur informasi, mengemas emosi kolektif, dan mengendalikan algoritma, sebuah negara mampu menggerakkan solidaritas, menanamkan kebencian, atau bahkan menciptakan kekacauan lintas batas.
Feed TikTok, reels Instagram, dan trending topic X (sebelumnya Twitter), telah menjelma menjadi ladang tempur baru, tempat opini publik dimanipulasi, dan polarisasi disulut secara masif.
Dalam lanskap konflik digital ini, informasi bukan sekadar pesan, namun juga berupa “senjata”. Framing menjadi taktik militer, dan algoritma adalah artileri yang menentukan seberapa luas dan seberapa dalam pesan dapat menghancurkan stabilitas sosial suatu negara.
Inilah tantangan besar yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ketika arus informasi semakin tak terkendali dan disinformasi menjadi senjata utama dalam perang kognitif, negara tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan militer atau diplomasi konvensional.
Komunikasi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara, bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi, tetapi untuk membangun daya tahan wacana nasional.
Indonesia perlu secara serius memperkuat kapasitas literasi media masyarakat, mendidik publik untuk memahami bias, framing, dan rekayasa pesan yang disisipkan dalam setiap konten yang viral.
Negara juga perlu menjadi contoh dalam membangun transparansi narasi dan etika digital, bukan malah menjadi bagian dari pengaburan informasi demi kepentingan politik jangka pendek. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton pasif dalam konflik narasi global yang terus menggerogoti batas-batas kesadaran kolektif masyarakat.
Ketika kebenaran dibentuk oleh siapa yang paling viral, bukan siapa yang paling jujur, maka Indonesia harus hadir sebagai jangkar stabilitas, sebagai negara yang tidak hanya menjembatani kepentingan diplomatik, tetapi juga menjaga integritas informasi di kawasan.
Dalam era perang informasi ini, mempertahankan perdamaian bukan lagi soal siapa punya rudal, tapi siapa yang punya kontrol atas narasi. Dan jika Indonesia gagal membangun ketahanan komunikasi nasional, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya arah wacana publik, tapi masa depan stabilitas regional kita sendiri. (*)
***
*) Oleh : Arif Budi Prasetya, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dan Mahasiswa Doktoral Universitas Airlangga.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |